Ambivalensi Hukuman Mati
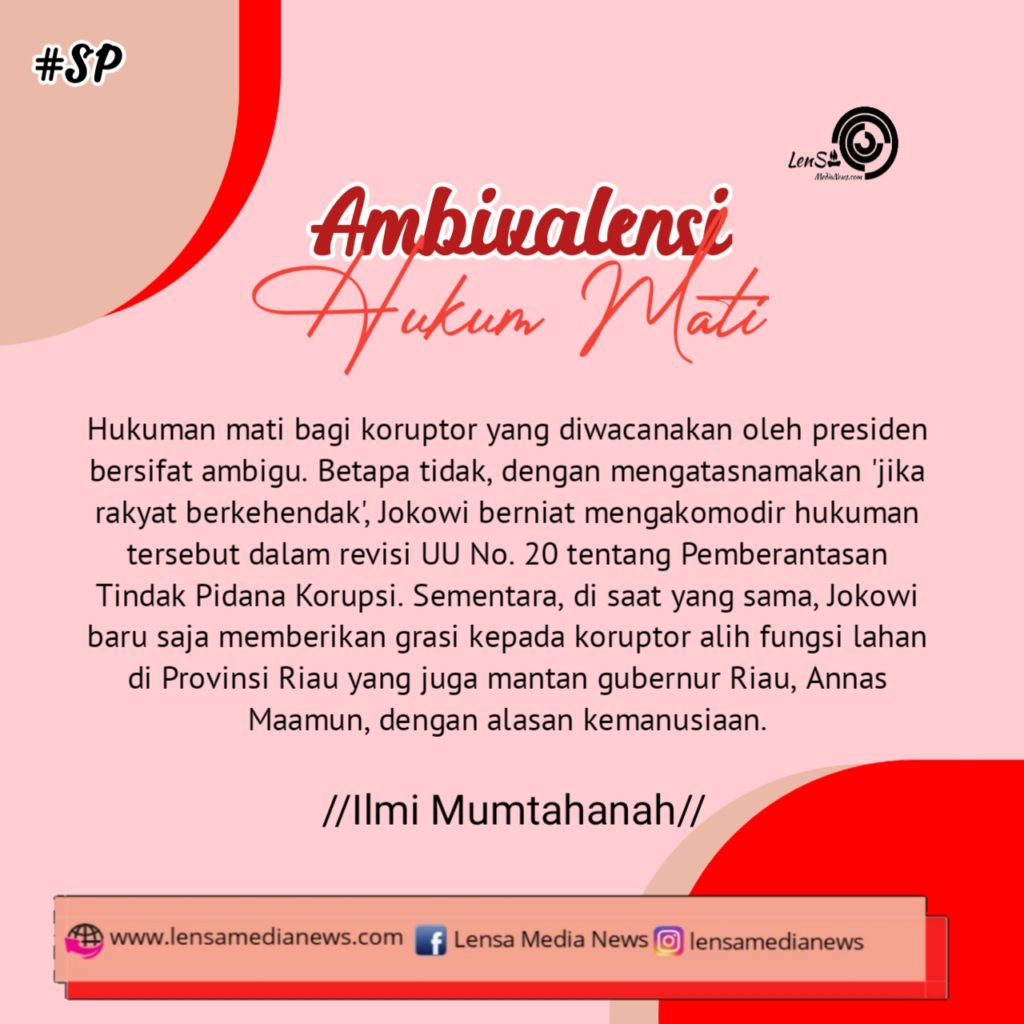
Hukuman mati bagi koruptor yang diwacanakan oleh presiden bersifat ambigu. Betapa tidak, dengan mengatasnamakan ‘jika rakyat berkehendak’, Jokowi berniat mengakomodir hukuman tersebut dalam revisi UU No. 20 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara, di saat yang sama, Jokowi baru saja memberikan grasi kepada koruptor alih fungsi lahan di Provinsi Riau yang juga mantan gubernur Riau, Annas Maamun, dengan alasan kemanusiaan.
Pun, ambiguitas tersebut juga terlihat dari revisi UU KPK yang dinilai melemahkan ruang gerak KPK. Kondisi pelemahan ini semakin terlihat tatkala presiden tidak menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU KPK yang baru. Sehingga, argumentasi yang menggelinding di tengah masyarakat cenderung menilai wacana itu hanya untuk membangun simpati publik.
Jika memang presiden serius ingin memberantas korupsi, seharusnya mengakomodir tindakan preventif dan kuratif untuk tindak kejahatan ini, bukan dengan membangun politik ketakutan yang tebang pilih.
Tindakan preventif dapat dilakukan dengan cara memastikan keluarga sebagai instrumen terkecil dalam negara untuk menanamkan nilai akidah dan syariah kepada anggota keluarganya. Sehingga mengkristal ketakwaan individu. Ketika diberi amanah, tidak akan berani berkhianat. Pun, ada kontrol dari masyarakat terhadap kebijakan publik.
Adapun tindakan kuratif, negara dipandang perlu mengembangkan jenis hukuman tersebut dari hudud (hukum syariat yang sudah jelas aturannya) kepada ta’zir (hukuman berdasarkan kebijakan hakim).
Mengingat, tindakan korupsi bisa berdampak pada penyengsaraan rakyat, penyelewengan wewenang, hingga membuat pemerintahan tidak bisa berjalan optimal. Sebab, dalam pandangan syariat, korupsi termasuk salah satu dosa besar, yaitu ghulul (penghianatan terhadap amanat rakyat). [LN/LM]
Ilmi Mumtahanah



